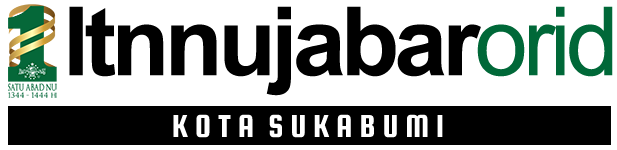Ketika Organisasi Jadi Alat Pemuas Ego
Ketika Organisasi Jadi Alat Pemuas Ego
Seri Ke 7
Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha

Salah satu problem serius dalam dunia kepemimpinan kontemporer, baik di lembaga pemerintahan, pendidikan, maupun organisasi keagamaan, adalah kecenderungan menjadikan organisasi sebagai alat pemenuhan ego pribadi. Organisasi yang idealnya menjadi wadah pelayanan publik dan pengembangan sosial, justru direduksi menjadi instrumen pembesaran citra dan ambisi pribadi pemimpinnya.
Gejala ini tidak berdiri sendiri. Ia berkembang dalam konteks budaya kekuasaan yang patronistik, di mana loyalitas terhadap individu lebih diutamakan daripada kesetiaan terhadap prinsip dan sistem. Dalam banyak kasus, pemimpin organisasi berupaya membentuk lingkungan yang tunduk dan homogen secara pandangan, untuk memantapkan legitimasi dirinya, bukan memperkuat organisasi.
Secara historis, kecenderungan semacam ini bisa ditemukan dalam organisasi politik maupun keagamaan sejak awal abad ke-20. Beberapa organisasi yang awalnya digerakkan oleh semangat kolektif berubah arah ketika kepemimpinannya berpusat pada figur tertentu. Dari sinilah mulai tumbuh apa yang disebut sebagai personalisasi organisasi, yakni ketika keberlangsungan lembaga bergantung pada satu orang.
Fenomena ini tentu tidak sehat. Ketika organisasi dikendalikan oleh hasrat egoistik, maka struktur internal menjadi timpang. Pengambilan keputusan tidak berbasis musyawarah atau data, melainkan kehendak tunggal pemimpin. Inilah bentuk distorsi manajerial, yang pada akhirnya akan melemahkan daya tahan dan kredibilitas organisasi itu sendiri.
Dalam kerangka kepemimpinan modern, idealnya organisasi memiliki sistem _check and balance_ yang kokoh. Namun dalam banyak praktik di Indonesia, sistem seperti ini tidak berjalan optimal karena terlalu banyak bergantung pada “kuasa simbolik” pemimpin. Orang-orang di sekitarnya menjadi tidak nyaman menyampaikan kritik karena khawatir dianggap melawan.
Prof. Azyumardi Azra sering mengingatkan bahwa demokratisasi organisasi adalah bagian dari reformasi intelektual. Pemimpin yang sehat secara etika tidak menjadikan organisasi sebagai panggung glorifikasi diri. Ia menjaga agar dinamika internal tetap terbuka, dan ia memosisikan dirinya sebagai fasilitator, bukan pusat perhatian.
Masalah akan semakin parah ketika pemimpin tidak hanya menjadikan organisasi sebagai alat, tetapi juga menjadikannya sebagai alat pembenaran. Kebijakan dikemas sedemikian rupa agar terkesan kolektif, padahal semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi pribadi. Bentuknya bisa bermacam-macam: pencitraan, manipulasi data, bahkan pengondisian opini publik internal.
Dalam jangka panjang, organisasi seperti ini kehilangan integritas. Profesionalisme tersisih oleh loyalitas sempit. Orang-orang yang kritis disingkirkan secara halus atau terang-terangan. Yang bertahan adalah mereka yang bersedia menyenangkan pemimpin, bukan yang mendorong perbaikan sistem. Ini tentu berbahaya bagi kelangsungan organisasi dan budaya kerja yang sehat.
Di sinilah pentingnya kesadaran etis dan intelektual dalam kepemimpinan. Organisasi tidak boleh disamakan dengan proyeksi diri. Jabatan bukan perpanjangan ego, melainkan tanggung jawab yang harus diemban secara kolektif. Seorang pemimpin seharusnya memposisikan dirinya dalam kerangka moral kepemimpinan, bukan sekadar keberhasilan citra.
Dalam Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Maknanya, kepemimpinan bukan ruang untuk membesarkan diri, tetapi medan pelayanan dan pengabdian kepada umat.
Penting bagi publik, termasuk para intelektual dan civil society, untuk terus mendorong model kepemimpinan yang menjunjung etika organisasi dan transparansi. Tanpa tekanan kultural dan kontrol sosial, pemimpin yang memiliki kecenderungan narsistik akan leluasa memperalat organisasi demi hasrat pribadinya.
Organisasi yang sehat tidak lahir dari kultus terhadap figur. Ia tumbuh dari sistem yang adil, proses yang terbuka, dan pemimpin yang rela berbagi peran. Hanya dengan cara itu, organisasi dapat bertahan, bukan hanya dalam masa kejayaan pemimpin, tetapi juga ketika ia sudah tidak lagi memegang tampuk kekuasaan.
—-000—-
*) Penulis adalah Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melakukan pengabdian sebagai:
– Ketua Umum Agerlip PP PGM Indonesia
– Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Sukabumi
– Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi
– Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi MUI Kota Sukabumi
– Ketua Komisi Bidang Pendidikan ICMI Kota Sukabumi
– Anggota Litbang, Perpustakaan, Kajian dan Kurikulum DKM Masjid Agung Kota Sukabumi
– Ketua FU-Warci (Forum Ukhuwah Islamiyah Warga Ciaul) Kota Sukabumi