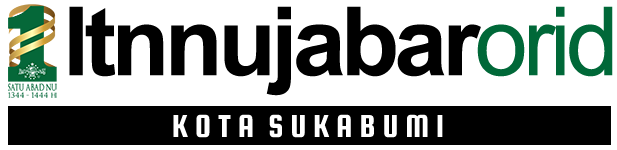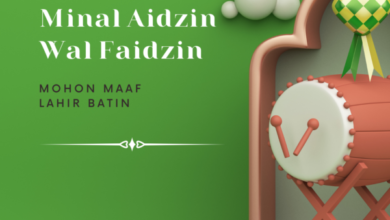Mengapa Pemimpin Narsistik Terlihat Memesona di Awal ?
Seri ke-5
Mengapa Pemimpin Narsistik Terlihat Memesona di Awal ?
Oleh: Mulyawan Safwandy Nugraha

Dalam sejarah kepemimpinan, banyak pemimpin yang awalnya memukau dengan retorika inspiratif, janji-janji mulia, atau karisma pribadi, tetapi lambat laun menunjukkan sisi gelap mereka. Pola ini terjadi hampir di semua bidang, mulai dari politik, pendidikan, hingga organisasi keagamaan dan sosial. Pesona awal sering kali hanya topeng yang menutupi ketidakmampuan, keserakahan, atau nafsu kekuasaan. Lalu, mengapa fenomena ini terus berulang? Salah satu penyebabnya adalah kecenderungan manusia untuk terpesona oleh citra yang dibangun, bukan substansi kepemimpinan yang sebenarnya.
Faktor psikologis memegang peranan penting dalam fenomena ini. Publik cenderung terbuai oleh narasi heroik atau janji perubahan instan, tanpa melakukan kritis terhadap kapasitas dan integritas sang pemimpin. Selain itu, efek “honeymoon period” membuat masyarakat memberi kelonggaran di awal kepemimpinan, sehingga kelemahan dan penyimpangan baru terlihat belakangan. Pemimpin yang cerdik memanfaatkan momen ini untuk membangun kultus individu, sambil secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Lingkungan yang tidak transparan dan lemahnya sistem checks and balances juga memperparah masalah ini. Di banyak institusi, pemimpin yang awalnya dianggap “penyelamat” justru diberikan kewenangan terlalu besar tanpa pengawasan memadai. Akibatnya, ketika kekuasaan terkonsentrasi, muncul penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau otoritarianisme. Sistem yang sehat seharusnya mampu mengoreksi penyimpangan sejak dini, tetapi minimnya partisipasi publik atau lemahnya hukum sering memberi ruang bagi pemimpin bermasalah untuk bertahan lama.
Untuk memutus siklus ini, masyarakat perlu lebih kritis dan proaktif dalam menilai pemimpin. Pesona awal harus diuji dengan track record, komitmen moral, dan kesediaan pemimpin untuk dikritik. Selain itu, institusi perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas, seperti audit independen, rotasi kekuasaan, atau partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Sejarah telah mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak lahir dari karisma semata, melainkan dari integritas, transparansi, dan sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa itu, pola pemimpin “musang berbulu domba” akan terus terulang.
Manusia sebagai makhluk simbolik cenderung mudah terpengaruh oleh penampilan, gaya bicara, dan narasi yang menyentuh emosi. Di sinilah pemimpin narsistik menemukan keunggulannya. Mereka mahir mengelola persepsi publik dengan tampil sempurna di setiap kesempatan. Kemampuan membaca situasi, menguasai diksi, dan memainkan bahasa tubuh membuat mereka terlihat meyakinkan. Lebih dari itu, mereka pandai menciptakan simbol-simbol harapan yang memikat massa. Namun, di balik pesona itu seringkali tersembunyi manipulasi, karena fokus mereka bukan pada substansi kepemimpinan, melainkan pada pemujaan terhadap diri sendiri.
Dalam psikologi, ini disebut impression management, yaitu seni mengelola kesan yang dikuasai pemimpin narsistik. Mereka bersinar di tahap awal dengan retorika memukau, penampilan sempurna, dan janji-janji grandiose. Namun, motifnya bukan pelayanan, melainkan pemenuhan narsisisme: kekaguman adalah oksigen mereka. Yang ditawarkan adalah ilusi, bukan solusi; gaya, bukan substansi. Problemnya, masyarakat sering terjebak sensasi tanpa mengecek realitas. Ketika panggung retorika usai, yang tersisa hanyalah performa kosong. Kepemimpinan sejati membutuhkan kedalaman, bukan sekadar pencitraan.
Jean Baudrillard menyebut era ini sebagai zaman simulakra, di mana citra sering lebih berpengaruh daripada realitas. Pemimpin narsistik berkembang pesat dalam iklim ini, karena mereka hanya perlu tampak kompeten—tidak harus benar-benar berkontribusi. Media sosial menjadi panggung utama: retorika dipoles, pencapaian dibesar-besarkan, dan kritik dihalau dengan narasi heroik. Mereka menjual fantasi, bukan solusi nyata. Ironisnya, publik kerap terjebak dalam ilusi ini, mengira pencitraan adalah bukti kapabilitas. Padahal, kepemimpinan sejati bukan soal pertunjukan, tapi aksi yang berdampak.
Fenomena pemimpin narsistik sebenarnya adalah cermin budaya masyarakat kita. Publik kerap terjebak dalam kultus kepribadian – lebih terpukau oleh gaya karismatik daripada track record nyata. Kita mudah tergoda oleh kisah dramatis “sang penyelamat”, sementara kerja keras tanpa pencitraan diabaikan. Media sosial memperparah hal ini dengan mengubah politik menjadi ajang kontes popularitas. Narsisme pemimpin tumbuh subur karena kita sebagai masyarakat memberinya panggung dan validasi. Problemnya bukan hanya pada individu, tapi pada sistem nilai yang mengagungkan penampilan di atas substansi.
Pemimpin narsistik memang kerap memukau di awal, namun kepemimpinan mereka ibarat bangunan tanpa fondasi. Daya tahannya pendek karena dibangun di atas pesona semu, bukan kepercayaan yang kokoh. Ketika tantangan organisasi semakin kompleks dan anggotanya mulai menuntut bukti konkret—bukan sekadar janji manis—topeng pun mulai terbuka. Mereka yang awalnya tampak percaya diri berubah defensif saat dikritik, lalu frustrasi ketika tak lagi dikagumi. Pada titik kritis, mereka justru menjadi penghambat kemajuan dengan sikap arogan dan tindakan merusak demi mempertahankan citra. Inilah ironi kepemimpinan narsistik: mereka yang awalnya dielu-elukan akhirnya menjadi beban organisasi.
Prof. Komaruddin Hidayat dalam banyak tulisannya sering menekankan pentingnya kesadaran spiritual dalam kepemimpinan. Ia menyebut bahwa pemimpin yang baik bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga jernih batinnya. Ia bisa menahan diri dari dorongan untuk menonjolkan ego, karena sadar bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan instrumen pembesaran diri.
Dalam Al-Qur’an, kita mengenal Fir’aun sebagai simbol pemimpin yang narsistik. Ia tidak hanya merasa paling hebat, tapi juga menuntut rakyat menyembahnya. Ia berkata: “Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain diriku.” (QS. Al-Qashash: 38). Ini bentuk puncak narsisme dalam kekuasaan, di mana pemimpin merasa sebagai pusat kebenaran dan tatanan.
Sayangnya, gaya seperti ini kadang dikagumi, terutama oleh masyarakat yang sedang mengalami krisis harapan. Pemimpin yang tegas, percaya diri, dan “paling tahu segalanya” dianggap sebagai penyelamat. Tapi tanpa disadari, harapan itu dijadikan alat legitimasi untuk membungkam kritik dan memperluas kontrol.
Oleh karena itu, dibutuhkan kedewasaan publik untuk tidak cepat terpesona. Kita perlu bertanya lebih dalam: apakah pemimpin ini hanya ingin dipuja, atau benar-benar ingin bekerja? Apakah ia membangun sistem, atau hanya membangun panggung? Apakah ia memberi ruang bagi orang lain, atau justru menghapus peran orang lain?
Pemimpin sejati tidak takut terlihat biasa. Ia bekerja dalam diam, dan biarkan hasil yang bicara. Ia tidak menjual diri, tapi mengabdi. Dan justru dari kesederhanaannya itu, muncul kewibawaan sejati. Maka Prof. Komar pernah menulis, “Pemimpin besar itu bukan yang membuat orang lain terpana, tetapi yang membuat orang lain tumbuh.”
Tugas kita adalah perkuat kesadaran kolektif: bahwa dalam memilih pemimpin, kita tidak sedang mencari bintang panggung, tapi penjaga perahu bersama. Kita butuh pemimpin yang tidak sekadar memesona di awal, tapi sanggup bertahan, mendengar, dan memperbaiki diri sepanjang jalan. Karena sesungguhnya, dalam jangka panjang, yang menyelamatkan bukanlah pesona, melainkan kejujuran, tanggung jawab, dan kebeningan hati.
============================
*) Penulis adalah Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melakukan pengabdian sebagai:
– Ketua Umum Agerlip PP PGM Indonesia
– Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Sukabumi
– Ketua Dewan Pendidikan Kota Sukabumi
– Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Kaderisasi MUI Kota Sukabumi
– Ketua Komisi Bidang Pendidikan ICMI Kota Sukabumi
– Anggota Litbang, Perpustakaan, Kajian dan Kurikulum DKM Masjid Agung Kota Sukabumi
– Ketua FU-Warci (Forum Ukhuwah Islamiyah Warga Ciaul) Kota Sukabumi